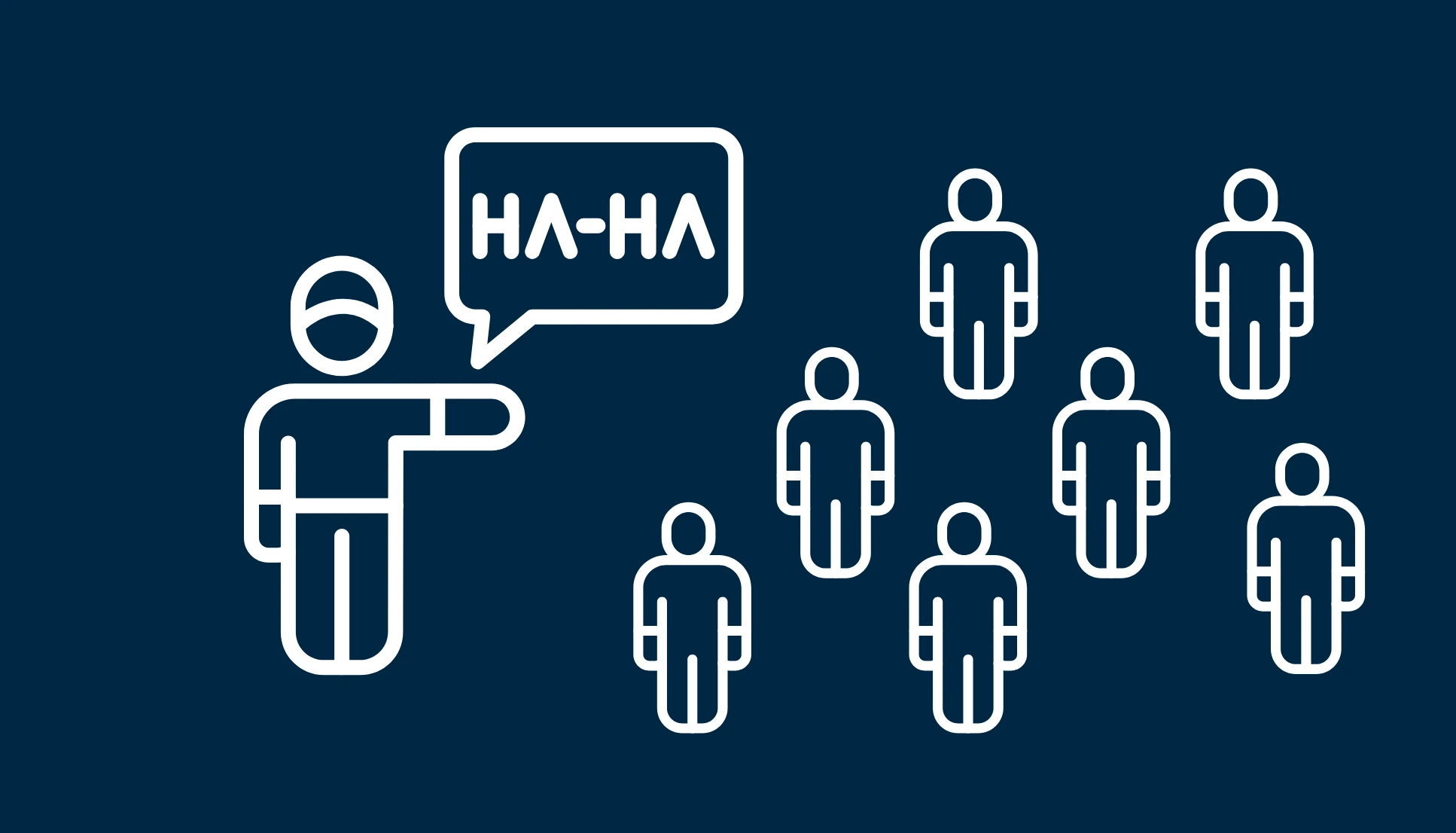Masyarakat Indonesia mempunyai kesenangan dalam menyebut sosok aktor politik dengan julukan-julukan yang mengarah ke olok-olok. Kekesalan melihat sandiwara politik dan ketidakbecusan perilaku aparat negeri ini banyak ditumpahkan ke istilah-isltilah satire. Mulai dari urusan bau badan, bocah kemlinthi, nepo-baby, doktor karbitan, mulyono, gemuk. Julukan-julukan ini cukup banyak mewarnai pembicaraan di media sosial, talk show di televisi, radio, maupun di surat kabar.
Julukan yang mengolok-olok atau name-calling ini sebenarnya adalah hal yang wajar dalam politik. Donald Trump, presiden ke 45 Amerika Serikat terkenal sering memberikan julukan terutama kepada lawan-lawan politiknya. Joe Biden, diberi julukan oleh Trump sebagai Crooked Joe, Joe Hiden, Sleepy Joe, dan Slow Joe. Hillary Clinton, lawan Trump sebelumnya, diberi julukan crazy Hillary dan lyin’ Hillary. Aksi Trump ini tentu saja mendapat kritik karena name-calling jelas berkonotasi negatif. Terdapat pula elemen perundungan didalamnya, yang dapat menyebabkan trauma dan rasa tidak percaya diri.
Name-calling adalah salah satu teknik propaganda dalam politik. Julukan sengaja disematkan untuk memberi impresi buruk terhadap individu, kepercayaan, kelompok, ras, maupun budaya tertentu tanpa ada dasar kebenaran. Sejarah komunikasi politik Indonesia juga penuh dengan name-calling, terutama sejak era pasca-reformasi yang meriah dengan komunikasi virtual. Kontestasi politik dengan menggunakan model olok-olok marak digunakan terutama menjelang masa pemilihan kepala negara maupun kepala daerah. Pemberian julukan yang mengarah pada isu SARA salah satu yang paling umum. Seperti kata: cebong, kampret, kadrun yang marak pada Pilpres 2019. Untuk individu, kita pernah mengenal julukan jenderal kardus, plonga-plongo, mukidi, jaenudin nachiro, pinokio, kerbau, dan lain-lain.
Deadnaming
Julukan olok-olok muncul melalui media sosial seiring gerakan protes menentang kebijakan politik yang tidak populer (baca: merugikan masyarakat). Julukan ini ramai diperbincangkan, dibagi dan disebarkan untuk bahan bercanda dan olok-olok. Julukan ini tidak muncul dari ruang hampa. Mulyono, misalnya. Merujuk pada nama kecil seseorang yang tidak lagi dipakai (deadnaming), Mulyono dimunculkan untuk mengolok-olok masa lalu seseorang. Seringkali berujung pada perendahan derajat dan deligitimasi, Muyono dipakai secara lugas oleh netizen dan politisi untuk menghujat.
Menurut Steve Forbes, editor in-chief Forbes Media, name-calling sudah waktunya diakhiri (Forbes, 2024). Dalam ulasannya terkait keriuhan kampanye presiden AS, dia mengatakan bahwa name-calling tidak akan memintarkan pemilih dan malah menjadi legitimasi terhadap aksi perundungan. Selain itu, umpatan dalam julukan dapat membelokkan isu-isu advokasi karena terlalu fokus pada satu individu yang diposisikan sebagai karakter antagonis.
Dalam artikel berjudul Political incivility: does name-calling works? (2023) Aaron Dusso dan Sydnee Perkins mencatat bahwa aktor-aktor politik yang menjadi korban name-calling tidak terpengaruh oleh julukan kasar dan kejam. Bahkan, julukan itu malah menjadi bumerang bagi yang memberikan. Simpati diberikan kepada yang diolok-olok. Sedangkan yang mengolok-olok malah tidak mendapatkan apa-apa.
Dusso dan Perkins melakukan survey terhadap 2016 orang Amerika pendukung dua partai: Demokrat dan Republik, untuk menentukan efek name-calling terhadap pemilih setelah mereka membaca berita terkait kampanye politik. Simulasi dilakukan dalam survey tersebut, dimana kandidat menyebut lawannya dengan julukan yang kejam dan merendahkan. Analisis data menemukan bahwa partisipan riset bersikap kritis terhadap pihak yang memberi julukan. Sementara penerima julukan tidak mengalami penurunan reputasi. Menariknya, hanya simpatisan Demokrat yang tidak menyetujui perilaku name-calling, darimanapun partainya. Sedangkan simpatisan Republik memandang name-calling tidak boleh dilakukan oleh Demokrat. Sedangkan kandidat Republik sah saja lakukan name-calling.
Name-calling yang dilakukan beramai-ramai bisa jadi menandakan kegeraman publik atas perilaku elit politik yang tidak dapat mereka jangkau. Ketika pintu dialog tertutup, maka name-calling akhirnya menjadi cara untuk mengekspresikan keresahan, sekaligus menjadi cara radikal untuk mendapat perhatian.
Yulina Goto (2022) dalam analisisnya terkait pilpres di Korea Selatan, menulis bahwa name-calling tidak berguna untuk masyarakat, namun penting untuk para politisi. Oleh karena itu, penyematan berbagai julukan harus selalu dicurigai sebagai komunikasi politik yang mengikutsertakan masyarakat. Budaya partisipatif masyarakat memungkinkan penyebaran julukan dan berkembang menjadi ajang perundungan yang tidak berujung.
Kritik dan satir
Perlu disadari, name-calling bukan melulu tentang olok-olok. Ada kritik yang dimunculkan melalui satir dan sindiran. Name-calling adalah representasi dari rasa muak masyarakat terkait kondisi, sikap, sifat dan ketidakteraturan politik yang terjadi di negeri ini. Dari kemunculannya di media sosial yang kemudian banyak dijadikan ucapan sinis di ruang-ruang publik, name-calling adalah sindiran langsung yang memang pahit rasanya.
Meski demikian, strategi propaganda politik dengan menggunakan name-calling juga perlu dipikirkan ulang sehingga tidak malah menjadi bagian dari budaya politik yang berbahaya bagi generasi muda Indonesia. Jangan-jangan keinginan untuk memperbaiki kondisi bangsa malah hanya mewariskan budaya olok-olok dan kesengitan yang tidak perlu kepada anak-anak muda kita?